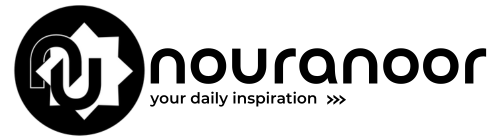nouranoor.com – Agree or Disagree (AoD) kali ini akan membahas satu fenomena yang sebenarnya tabu namun faktanya sudah umum dilakukan, yaitu “living together”. Istilah ini sudah tidak asing tentunya di era ini, terutama di kalangan anak muda.
“Living together” atau kohabitasi atau beberapa dekade lalu disebut juga kumpul kebo. Makna dari istilah tersebut merupakan fenomena di mana sepasang kekasih tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan formal.
Mengapa fenomena ini bisa tren bahkan menjadi rahasia umuma? Yups, jawabannya satu yaitu media sosial. Kita tidak bisa memungkiri, sumber atau rujukan informasi anak muda saat ini 90% dari media sosial.
Apa yang menjadi tren dan viral di media sosial pasti banyak dari mereka yang mengikuti. Sedikit sekali yang mempertimbangkan dampak jangka panjang hanya dari sekadar FOMO. Itulah mengapa apapun yang viral di media sosial sangat masif pengikutnya.
Di berbagai platform media sosial, pembahasan fenomena “living together” terkesan sudah umum bahkan ada beberapa influencer yang menyatakan melakukannya. Hal ini semakin memperkuat fenomena ini semakin menjadi tren di kalangan anak muda.
“Living together” selalu sering tergambar sebagai hubungan yang penuh keromantisan. Namun banyak yang belum menyadari bahwa ada dampak besar yang harus mereka tanggung dengan memilih mengikuti tren ini.
Faktor-Faktor Memilih Living Together
Di balik fenomena “living together”, terdapat beberapa faktor yang mendorong anak muda untuk mengikuti fenomena ini. Mulai dari faktor sosial, finansial, dan juga mental menjadi alasannya.
Jika melihat dari faktor sosial, pertama tentu saja bagian dari FOMO (fear of missing out). Ketika anak muda berada di lingkungan yang terbiasa dengan hubungan bebas, tentunya sadar atau pun tidak akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebiasaan di lingkuangannya.
Faktor kedua, semakin maraknya anak muda yang lebih individual. Terutama di kota-kota besar, individualisme sudah menjadi umum sehingga ketika melihat ada yang memilih “living together”, orang sekitar akan acuh saja. Tentu saja hal ini membuat tren tersebut semakin umum.
Faktor ketiga cukup klasik, yaitu sebagai uji coba sebuah hubungan. Tinggal seatap dengan pasangan sering dianggap sebagai solusi untuk mengenal satu sama lain sebelum menjalani hubungan yang terikat secara formal.
Kemudian jika berdasarkan faktor finansial, karena merasa belum mapan. Di era saat ini, untuk menikah saja terkadang harus mengeluarkan biaya yang sangat fantastis belum lagi untuk biaya hidup setelahnya. Itulah mengapa memilih “living together” sebagai jalan ninja, yang terkesan lebih hemat biaya.
Dari sisi faktor mental, pertama karena ketidakmatangan mental untuk menikah. Merasa belum mampu memikul tanggung jawab pernikahan, sehingga lebih sepakat untuk sekadar tinggal bersama. Kedua, bisa jadi karena trauma akan kehidupan pernikahan orang terdekatnya (bahkan orang tuanya sendiri). Hal ini yang membuat mereka enggan untuk serius membangun komitmen dalan ikatan pernikahan.
Faktor-faktor ini tentu saja tidak bisa menjadi pembenaran akan fenomena “living together”. Apapun alasannya tentu saja melanggar hukum, norma adat dan juga agama.
Living Together = Komitmen Semu
Jika berpikir “living together” sebagai satu jalan untuk memberikan kepastian hubungan atau membangun sebuah komitmen bersama pasangan rasanya tidak tepat.
Ketika memilih hidup bersama tanpa ikatan formal, tentunya sudah harus siap dengan segala konsekuensinya. Salah satunya akan ada masa hubungan yang tidak berkembang, dan akhirnya stuck di satu sisi.
Mengutip dari artikel The Conversation (2024), pasangan yang terlalu cepat tinggal bareng sering kehilangan masa “explore” yang penting banget buat membangun hubungan yang kuat. Dan ketika ada masalah besar muncul, mereka bingung cara menghadapinya karena merasa hubungan mereka udah terlalu “serius” untuk mundur, tapi juga belum cukup matang untuk lanjut ke tahap berikutnya.
Inilah yang jarang dipertimbangkan saat memilih tinggal bersama, bahkan berpikir bisa membangun komitmen serius dengan cara ini. Padahal itu merupakan pemikiran yang keliru, yang ada hanya komitmen semu.
“Living together” akan tetap terlihat atau terasa baik-baik saja saat pasangan tetap memiliki ekspektasi yang sama. Namun ketika salah satunya sudah memiliki ekspektasi yang lebih tinggi maka semuanya akan segera berubah 180 derajat.
Maka patut disadari sejak awal, ada lebih banyak risiko dari pada manfaat positifnya dari tren ini. Risikonya antara lain stigma sosial, tidak ada ruang privasi, hingga ketergantungan emosional yang tidak sehat.
Kesimpulan
Dari fenomena “living together” sebenarnya kita bisa berkaca dari berbagai kasus, terutama yang belum lama terjadi dari pasangan yang berakhir tragis di mutilasi di Jawa Timur.
Berdasarkan informasi yang beredar mereka sudah tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan sekitar 5 tahun. Namun hubungan itu berakhir tragis, akibat sering cek-cok berkepanjangan pasangan laki-lakinya tega mengakhiri nyawa pasangan perempuannya dengan cara yang sadis.
Sudah jelas memilih tinggal bersama tanpa ikatan formal bukanlan solusi tepat untuk mengenal pasangan satu sama lain. Terutama untuk kita yang cukup kental budaya asia/ budaya timurnya, tren seperti ini rasanya tidak akan cocok sampai kapan pun.
Jika ingin membangun hubungan yang sehat, bisa memulai dengan diskusi tentang pandangan masing-masing mengenai tujuan menjalin hubungan. Dari sini akan mulai terlihat pattern atau arah nya, serius atau sekadar main-main.
Kalau baru sekadar main-main dan jelas pasangan belum mau atau mampu memegang tanggung jawab, jangan melangkah lebih jauh untuk tinggal bersama apalagi tanpa ikatan.
Balik lagi jika berkaca dari kasus yang pernah ada, mostly pihak perempuan yang lebih sering menjadi korban. Bukan tanpa alasan, ini karena perempuan mudah dieksploitasi perasaannya.
Kesimpulannya secara umum tentu tidak setuju (disagree) dengan tren “living together” ini. Alasannya cukup jelas karena lebih banyak risikonya dari pada dampak positifnya.
Namun bagi yang masih mengikuti tren ini, untuk lebih sering-sering evaluasi bersama pasangan terkait tujuan, kesehatan, dan kesiapan risiko yang menghantui. Jika tidak sama-sama sejalan, mungkin saja petaka seperti kasus di atas terjadi.
Poin sederhanyanya seperti ini, tinggal bersama tanpa ikatan itu jelas sebuah keputusan besar. Dan setiap keputusan besar pasti ada tanggung jawabnya. Kita tidak bisa sekadar berpikir, “Gue cinta dia, jadi yaudah tinggal bareng.” Cinta penting, tapi kematangan emosi, kesiapan mental, dan kesepakatan nilai jauh lebih krusial.